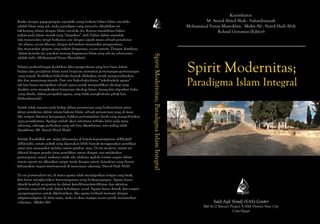
MASIH segar dalam ingatan kita seorang pejuang kemanusiaan yang bercita-cita menyatukan antara Timur dan Barat. Muhammad Iqbal, itulah nama pejuang yang sangat populer sebagai representasi modernisasi Islam di India, dan bapak spiritual negara Islam di Pakistan. Iqbal sudah mencurahkan segala upayanya demi satu tujuan: mewujudkan adanya saling pengertian antara Timur dan Barat. Menurutnya, secara penalaran, dunia Barat boleh dibilang lebih maju dari dunia Timur, tetapi kalau ditinjau dari aspek moral transendental sudah berlari begitu jauh hingga hampir memasuki pintu gerbang kehampaan. Sedangkan Timur yang tertimbun dalam jurang spiritualisme, sudah lama pula berdiam diri tanpa dinamika (Syafi`i Ma`arif: Muhammad Iqbal dan Suara Kemanusiaan dari Timur). Upaya yang dilakukan oleh Iqbal kiranya merupakan sebentuk keprihatinan melihat konflik berkepanjangan antara Barat dengan Timur.
Sebenarnya, konflik antara Barat dan Timur, Islam khususnya, telah berlangsung sejak berabad-abad yang silam, sejak Islam melakukan penaklukan besar-besaran, seperti digambarkan dalam prolog buku ini, terhadap Syam, Mesir, Persia, Andalusia, Eropa Timur, Asia kecil serta segenap ekspedisi misioner yang dilakukan ke belahan dunia lain yang meliputi benua India, bahkan hampir sebagian besar benua Asia. Sebagaimana lazimnya watak manusia, yang tidak mudah melupakan kekejaman orang lain terhadap dirinya, penaklukan yang dilakukan Islam secara sengaja dijadikan tumpukan memori yang pada akhirnya bermetamorfosa menjadi “dendam kesumat” oleh orang-orang Eropa. Berbekal “dendam” inilah mereka kemudian belajar dan membenahi diri dengan sungguh-sungguh. Dan pada episode berikutnya, cita-cita untuk menjadi bangsa digdaya benar-benar menjadi kenyataan. Di saat kekuatan-kekuatan Islam melemah, sebaliknya mereka sudah melangkah jauh meninggalkan masa lalunya yang kelam menuju apa yang kita kenal dengan zaman modern. Sebutan “bangsa penakluk” telah berpindah kepada mereka. Eropa dan Barat telah menjadi bangsa-bangsa raksasa yang sulit dikalahkan.
Seperti biasa, yang kuat akan berbuat semena-mena kepada yang lemah. Kita saksikan, paling tidak sejak awal-awal tahun 90-an hingga sekarang, bagaimana Barat dengan kekuatannya, melalui ucapan dan tulisan sebagian ilmuannya, melalui media-media informasi yang dimilikinya, menyebarkan “kebohongan” bahwa Islam —setelah hancurnya Uni Soviet— merupakan musuh terbesar bagi kedamaian dunia, bahaya terbesar yang mengancam apa yang kita kenal dengan “dunia bebas”. Mungkin kita masih ingat bagaimana seorang Huntington secara “cerdas” menggambarkan Islam sebagai musuh utama Barat dalam bukunya, Clash of Civilization. Saya berkeyakinan, bahwa Islam, atau agama apapun, dengan sendirinya, tidak mungkin menanamkan permusuhan. Dari itu, permusuhan terhadap Barat harus dipahami dalam konteks sejarah yang di dalamnya masyarakat dunia ketiga hidup, Islam ataupun non-Islam, serta merasakan keterbelakangannya dari negara-negara industri yang maju dan ketundukannya, sebagaimana masyarakat tersebut, walaupun tertatih-tatih, berusaha untuk lepas dari keterbelakangan dan ketundukan itu. Ini berarti bahwa Islam hakikatnya bukanlah ancaman bagi dunia, justru sebaliknya: mayoritas kaum Muslimin saat ini merasa didhalimi dan diancam. Jika perasaan semacam ini kadang-kadang menyebabkan munculnya hal-hal yang irrasional atau aksi-aksi radikal —terhadap orang asing atau para touris, secara khusus di negara-negara yang mayoritas masyarakatnya adalah Muslim— maka yang paling bertanggung-jawab seharusnya adalah sebagian kekuatan Barat yang terlalu hegemonik terhadap dunia, mengkhianati nilai-nilai ideal yang selama ini digembar-gemborkan (seperti hak penentuan nasib, demokrasi dan hak-hak kemanusiaan dll.) serta menerapkan standar-standar ganda yang malah membahayakan kemaslahatan masyarakat-masyarakat dunia ketiga, khususnya masyarakat Islam. Bukti paling kongkret dari kedhaliman yang terjadi adalah tragedi Bosnia, tragedi Palestina, tragedi Irak dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Andaikata tragedi-tragedi ini dan semacamnya melahirkan reaksi-reaksi keras melalui gerakan-gerakan fundamentalisme, orang-orang Barat tidak bisa dengan serta-merta menganggap Islam sebagai musuh, justru hal ini harus memancing mereka untuk mempelajari faktor-faktor gerakan-gerakan radikal tersebut, mendorong untuk mengkaji ulang standar-standar ganda mereka sendiri, berusaha untuk merubah sikap terhadap kaum Muslimin dan menjelaskan bahwa mereka datang untuk memahami, bukan untuk memerangi.
Kenyataan yang ada di hadapan kita memperlihatkan, betapa umat Islam tidak saja terancam dari luar, dari dalam mereka sendiri malah muncul masalah yang sangat serius, perselisihan antarkelompok yang juga tidak kunjung selesai, sehingga membuat mereka terkapling-kapling, hanya gara-gara persoalan yang sangat sepele.
Saya melihat apa yang dilakukan kawan-kawan SAS (Said Agil Siradj) Center ini —termasuk saya sebagai salah seorang penulis— sebenarnya adalah upaya integralisasi kesadaran antara pelbagai mainstream atau mazhab yang ada dalam Islam (tawhîd al-wa`y al-dînî). Dalam buku ini, kita lihat misalnya urutan makalah yang masing-masing bertemakan teologi, fikih, tasawuf, dan politik. Dari urutan ini terlihat dengan jelas, teologi sengaja didekatkan dengan fikih, sedangkan tasawuf didekatkan dengan politik. Di sini, sebetulnya, titik penyatuannya berada pada teologi dan tasawuf, dan titik perselisihannya terletak pada fikih dan politik. Dengan kata lain bahwa, teologi membahas tentang masalah-masalah ketuhanan, sementara fikih adalah pelbagai pendapat manusia mengenai kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang menjelaskan tentang `ibâdât (=hubungan manusia dengan Tuhan) atau mu`âmalât (=hubungan manusia dengan manusia). Saya tetap percaya bahwa Islam merupakan sekumpulan ajaran Tuhan yang diturunkan kepada seluruh makhluk, dan saya yakin seluruh kaum Muslimin sepakat dengan saya. Hanya saja, ajaran-ajaran Tuhan tersebut tidak akan dikenal oleh manusia kecuali melalui penafsiran yang tak lain adalah aktivitas manusia itu sendiri. Karena kualitas akal manusia berbeda-beda, maka hasil penafsirannya pun tidak seragam. Sehingga tidak heran kalau setiap kelompok atau mazhab mempunyai pendapat sendiri-sendiri mengenai tata cara pelaksanaan `ibâdât dan mu`âmalât tadi. Namun demikian, teologi yang dipakai seluruh umat Islam, betapapun terkadang terdapat perbedaan dalam menggambarkan entitas Tuhan, toh mereka tetap mengakui teologi tauhid, yaitu peng-esaan Allah swt.. Ini artinya, betapapun fikih yang dianut berbeda-beda, tetapi Tuhan tetap satu.
Di dalam buku ini juga, seperti saya singgung di atas, tasawuf didekatkan dengan politik. Tasawuf adalah upaya manusia untuk membersihkan atau menyucikan segala noda dan dosa yang menempel serta mengotori jiwa, yang tujuan akhirnya adalah mendekati, berdialog dan menyatu dengan Tuhan. Dan pendekatan yang dilakukan bukan dengan teki-teki rasional sebagaimana para ahli kalam, melainkan dengan cinta yang muncul dari hati yang suci. Adapun politik adalah “alat” yang senantiasa digunakan untuk mendapatkan kekuasaan, baik secara halus maupun dengan kekerasan. Perjalanan sejarah Islam selalu saja diwarnai dengan konflik antarkelompok, terutama Syi`ah dan Ahl al-Sunnah, yang pada akhirnya dimenangkan oleh Ahl al-Sunnah, karena kelompok ini berhasil memegang kendali politik. Kesuksesan secara politik ini lantas mereka campur-aduk dengan kebenaran dogmatik agama, sehingga secara agresif mereka berhasil memonopoli pemahaman Islam yang benar (=ortodoksi), tentu saja demi kepentingan mereka sendiri. Sementara kelompok yang tidak sealiran dilempar begitu saja ke jurang heretodoksi.
Namun, di tengah-tengah percaturan politik yang nampak tidak adil itu, terdapat sejumlah orang yang secara sengaja mengasingkan diri, mencari sepercik kedamaian pada sudut-sudut dunia. Tuhan yang bagi manusia biasa mustahil dicapai, coba mereka hadirkan dalam jiwa, mengiringi setiap deraian nafas, tuk hapuskan segala dahaga, dan mengisi pelbagai macam kehampaan. Mereka adalah para sufi yang secara tulus menyembah Tuhan, menyembah-Nya dengan segenap cinta. Setiap saat mereka berdialog dengan-Nya, menumpahkan kegelisahan-kegelisahan batin, mencurahkan berjuta kerinduan yang menghimpit.
Mereka inilah yang kemudian mengajak manusia untuk instrospeksi diri, melihat siapa dirinya yang sesungguhnya, bertanya apa sebenarnya tujuan hidupnya. Politik bukanlah tujuan hidup, ia tak lebih dari sekedar alat. Pada dasarnya memang tidak salah seseorang berkecimpung dalam dunia politik, hanya saja jika pilihan hidupnya diimbangi dengan sikap kritis, karena bagaimanapun politik adalah buatan manusia yang relatif, serba kekurangan. Relativitas politik sangat berpotensi memunculkan pelbagai konflik berdarah. Di sinilah spirit sufistik sangat diperlukan demi mewujudkan adanya sikap saling mengerti, saling menerima dan saling menghormati satu sama lain, sehingga integralitas umat yang selama ini menjadi harapan nantinya akan benar-benar tercapai.
Tentunya spirit sufistik yang dimaksud bukanlah spirit yang “mandul”, atau spirit yang selama ini diasumsikan sebagai penyebab mundurnya peradaban agama dan manusia, tetapi spirit yang dinamis dan menggerakkan. Bukan spirit yang membuat seseorang berhenti menjalin kontak dengan sesamanya, melainkan spirit yang mempunyai kepekaan sosial yang tinggi.
Kalau ditinjau lebih jauh, dalam buku ini kita akan melihat banyak sekali indikasi yang mengarah pada proses terciptanya ijtihad baru, sebuah aktivitas penalaran yang selama ini ramai dibincangkan oleh para tokoh Islam, sebut saja di antaranya adalah Muhammad Iqbal. Menurutnya “ijtihad” merupakan prinsip gerakan dalam Islam. Gerakan yang dimaksud adalah gerakan ke arah sesuatu yang lebih baik atau yang lebih maju. Sebab ijtihad sendiri artinya berusaha dengan sungguh-sungguh. Dalam istilah fikih kata ini berarti berusaha dengan tujuan melakukan suatu penalaran rasional yang bebas perihal suatu persoalan hukum. Kiranya ini sesuai dengan semangat yang terkandung dalam sebuah ayat al-Qur’an yang berbunyi: “Dan kepada mereka yang berusaha kami tunjukkan jalan kami.” Juga ayat lain yang senada: “Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali mereka mau merubahnya sendiri.” Ini dipertegas oleh sebuah hadis yang menceritakan tentang pengangkatan Mu`adz sebagai gubernur Yaman oleh Nabi. Diceritakan bahwa Nabi bertanya kepada Mu`adz bagaimana seyogyanya ia mengambil keputusan mengenai persoalan yang dihadapinya. “Saya akan menjalankan hukum berdasarkan al-Qur’an,” kata Mu`adz. “Tapi jika dalam al-Qur’an tidak ada petunjuk bagimu?” “Saya akan jalan dengan berpijak pada Sunnah.” “Tapi kalau dalam Sunnah juga tidak ada?” “Saya akan berusaha menurut penalaran saya sendiri.”
Dua ayat sebelumnya, secara tidak langsung, menyuruh kita untuk senantiasa berusaha tanpa henti. Sebab hanya dengan berusaha Tuhan akan mengulurkan “tangan-Nya” membantu kita. Sementara hadis setelahnya menjelaskan tentang pedoman yang harus dijadikan pijakan dasar dalam mengarungi kehidupan. Hubungan antara kedua ayat dengan hadis tersebut menjadi sangat jelas, bahwa manusia harus berusaha untuk terus berubah, bergerak ke arah yang lebih baik. Dan dalam menjalani hidupnya, manusia memerlukan pedoman yang bisa dijadikan sandaran. Pedoman tersebut bisa berupa teks-teks agama, seperti al-Qur’an dan hadis, tapi ini saja tidak cukup, manusia masih membutuhkan pedoman lain yang tidak kalah pentingnya dari sekedar teks-teks agama, yaitu akal. Nabi tidak akan bertanya lebih lanjut perihal apa yang harus dilakukan jika ternyata al-Qur’an dan hadis sudah mencukupi dalam proses perumusan hukum. Justru pertanyaan terakhir yang beliau ajukan itu menunjukkan bahwa al-Qur’an dan hadis masih memiliki keterbatasan. Pada titik inilah akal mempunyai peran yang sangat signifikan. Untuk mengaktivasi akal, ijtihad yang oleh Iqbal dianggap sebagai “prinsip gerakan” harus diberlakukan, tidak boleh tidak.
Di samping itu, buku ini juga menyajikan semacam dekonstruksi-rekonstruksi; rancang-bangun teologi, fikih, tasawuf dan politik sengaja dikritik dengan menelusuri latar belakang sejarahnya, setelah itu baru kemudian dilakukan “pembangunan kembali” agar sesuai dengan semangat-semangat modernitas. Nah, setidaknya, “Spirit Modernitas; Paradigma Islam Integral” sudah cukup mewakili untuk menjadi judul buku yang sangat sederhana ini.
************
Sebagian orang barangkali ada yang bertanya, kenapa kami harus capek-capek menulis artikel untuk kemudian dikodifikasikan dalam sebuah buku? Kita perlu melihat masa lalu kita dengan kaca mata masa kini, bukan sebaliknya. Sebagian dari kita ada yang senang mewarnai kehidupan kita saat ini dengan hiasan-hiasan masa lalu, ini adalah sikap yang tidak selaras dengan logika sejarah. Perlu diingat, di hadapan kita ada dua peradaban, peradaban “nenek moyang” kita di satu sisi, dan peradaban masa kini di sisi lain, akan tetapi kedua peradaban ini saling bertolak belakang, sehingga kita tidak mungkin bisa menerima keduanya sekaligus. Peradaban pertama, secara mendasar berkutat pada moralitas-moralitas perilaku yang diridhai Tuhan Yang Maha Esa, sementara peradaban kedua berkutat pada saint berikut bidang-bidang pekerjaan yang dihasilkannya. Peradaban pertama adalah peradaban “teks”, sedang yang kedua adalah peradaban “alat”. Peradaban pertama menghasilkan manusia-manusia yang seragam, adapun yang kedua menghasilkan pabrik-pabrik serta roket-roket yang menari-nari di angkasa. Di sini kita dituntut supaya mampu menyelaraskan keduanya. Ini adalah hal yang tidak pernah ditargetkan oleh Barat, sebab ia hanya memiliki satu peradaban; peradaban modern seperti yang kita lihat saat ini. Kita mengambil dari peradaban Barat apa yang bisa kita ambil, bahwa kita kalau ingin berubah dan membentuk peradaban baru, kita harus merubah standar-standar atau pola-pola yang sudah tidak sesuai dengan kehidupan kita saat ini, maka demi terwujudnya perubahan itulah kami menulis.
Perlu disampaikan di sini, bahwa penulis itu bisa dikelompokkan menjadi dua, sebagian ada yang menulis apa yang ingin dibaca oleh banyak orang, sebagian yang lain ada yang menulis apa yang harus diketahui oleh para pembaca. Kelompok pertama menulis dengan tujuan mencari kerelaan dari para pelanggannya, sedang kelompok kedua hanya memberikan arahan dan petunjuk meskipun harus menuai kemarahan dan kebencian dari banyak orang. Kelompok pertama adalah pemegang cermin agar pada permukaannya bisa memantulkan gambaran manusia sebagaimana adanya, adapun kelompok kedua adalah pemegang lampu guna menerangi jalan di hadapan manusia; jalan baru yang sebelumnya kurang atau bahkan tidak terpikirkan sama sekali (=allâ mufakkar fîhi). Dan kami telah memilih —meskipun sulit— untuk menjadi seperti kelompok kedua, sebab kami senantiasa berusaha menuju ke arah tatanan kehidupan yang lebih baru.
Tak soal kami menulis untuk siapa, kami tidak punya hak untuk memilih pembaca, kami hanya menulis bagi siapa saja yang sudi membacanya. Dan kami tidak bisa mengklaim bahwa kami mampu melenyapkan segenap kegelisahan yang ada di masyarakat, bahkan mungkin, dengan apa yang kami tulis ini, justru akan menambah kegelisahan-kegelisahan lain. Kami tidak ingin menjadi penjilat atau mencari muka, jika kami melihat masyarakat —yang kami adalah bagian dari mereka— merasa perlu untuk melakukan perubahan, maka kami persembahkan buku ini dalam rangka menunaikan amanah pemikiran. Perkara nanti apa yang kami tulis salah atau benar, itu adalah soal lain, yang jelas kami telah berusaha menorehkan pemikiran kami dengan penuh ketulusan.
Itulah sekedar pengantar dari saya selaku editor. Mewakili kawan-kawan SAS Center, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran proses penerbitan buku ini. Kami juga mohon maaf jika dalam buku ini terdapat banyak sekali kekurangan, justru hal itu menunjukkan bahwa kami hanyalah manusia biasa yang tak kebal kesalahan. Akhirnya kritik dan saran konstruktif tetap kami tunggu dari para pembaca, biar untuk ke depan kami bisa berbuat yang lebih baik.
Sebenarnya, konflik antara Barat dan Timur, Islam khususnya, telah berlangsung sejak berabad-abad yang silam, sejak Islam melakukan penaklukan besar-besaran, seperti digambarkan dalam prolog buku ini, terhadap Syam, Mesir, Persia, Andalusia, Eropa Timur, Asia kecil serta segenap ekspedisi misioner yang dilakukan ke belahan dunia lain yang meliputi benua India, bahkan hampir sebagian besar benua Asia. Sebagaimana lazimnya watak manusia, yang tidak mudah melupakan kekejaman orang lain terhadap dirinya, penaklukan yang dilakukan Islam secara sengaja dijadikan tumpukan memori yang pada akhirnya bermetamorfosa menjadi “dendam kesumat” oleh orang-orang Eropa. Berbekal “dendam” inilah mereka kemudian belajar dan membenahi diri dengan sungguh-sungguh. Dan pada episode berikutnya, cita-cita untuk menjadi bangsa digdaya benar-benar menjadi kenyataan. Di saat kekuatan-kekuatan Islam melemah, sebaliknya mereka sudah melangkah jauh meninggalkan masa lalunya yang kelam menuju apa yang kita kenal dengan zaman modern. Sebutan “bangsa penakluk” telah berpindah kepada mereka. Eropa dan Barat telah menjadi bangsa-bangsa raksasa yang sulit dikalahkan.
Seperti biasa, yang kuat akan berbuat semena-mena kepada yang lemah. Kita saksikan, paling tidak sejak awal-awal tahun 90-an hingga sekarang, bagaimana Barat dengan kekuatannya, melalui ucapan dan tulisan sebagian ilmuannya, melalui media-media informasi yang dimilikinya, menyebarkan “kebohongan” bahwa Islam —setelah hancurnya Uni Soviet— merupakan musuh terbesar bagi kedamaian dunia, bahaya terbesar yang mengancam apa yang kita kenal dengan “dunia bebas”. Mungkin kita masih ingat bagaimana seorang Huntington secara “cerdas” menggambarkan Islam sebagai musuh utama Barat dalam bukunya, Clash of Civilization. Saya berkeyakinan, bahwa Islam, atau agama apapun, dengan sendirinya, tidak mungkin menanamkan permusuhan. Dari itu, permusuhan terhadap Barat harus dipahami dalam konteks sejarah yang di dalamnya masyarakat dunia ketiga hidup, Islam ataupun non-Islam, serta merasakan keterbelakangannya dari negara-negara industri yang maju dan ketundukannya, sebagaimana masyarakat tersebut, walaupun tertatih-tatih, berusaha untuk lepas dari keterbelakangan dan ketundukan itu. Ini berarti bahwa Islam hakikatnya bukanlah ancaman bagi dunia, justru sebaliknya: mayoritas kaum Muslimin saat ini merasa didhalimi dan diancam. Jika perasaan semacam ini kadang-kadang menyebabkan munculnya hal-hal yang irrasional atau aksi-aksi radikal —terhadap orang asing atau para touris, secara khusus di negara-negara yang mayoritas masyarakatnya adalah Muslim— maka yang paling bertanggung-jawab seharusnya adalah sebagian kekuatan Barat yang terlalu hegemonik terhadap dunia, mengkhianati nilai-nilai ideal yang selama ini digembar-gemborkan (seperti hak penentuan nasib, demokrasi dan hak-hak kemanusiaan dll.) serta menerapkan standar-standar ganda yang malah membahayakan kemaslahatan masyarakat-masyarakat dunia ketiga, khususnya masyarakat Islam. Bukti paling kongkret dari kedhaliman yang terjadi adalah tragedi Bosnia, tragedi Palestina, tragedi Irak dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Andaikata tragedi-tragedi ini dan semacamnya melahirkan reaksi-reaksi keras melalui gerakan-gerakan fundamentalisme, orang-orang Barat tidak bisa dengan serta-merta menganggap Islam sebagai musuh, justru hal ini harus memancing mereka untuk mempelajari faktor-faktor gerakan-gerakan radikal tersebut, mendorong untuk mengkaji ulang standar-standar ganda mereka sendiri, berusaha untuk merubah sikap terhadap kaum Muslimin dan menjelaskan bahwa mereka datang untuk memahami, bukan untuk memerangi.
Kenyataan yang ada di hadapan kita memperlihatkan, betapa umat Islam tidak saja terancam dari luar, dari dalam mereka sendiri malah muncul masalah yang sangat serius, perselisihan antarkelompok yang juga tidak kunjung selesai, sehingga membuat mereka terkapling-kapling, hanya gara-gara persoalan yang sangat sepele.
Saya melihat apa yang dilakukan kawan-kawan SAS (Said Agil Siradj) Center ini —termasuk saya sebagai salah seorang penulis— sebenarnya adalah upaya integralisasi kesadaran antara pelbagai mainstream atau mazhab yang ada dalam Islam (tawhîd al-wa`y al-dînî). Dalam buku ini, kita lihat misalnya urutan makalah yang masing-masing bertemakan teologi, fikih, tasawuf, dan politik. Dari urutan ini terlihat dengan jelas, teologi sengaja didekatkan dengan fikih, sedangkan tasawuf didekatkan dengan politik. Di sini, sebetulnya, titik penyatuannya berada pada teologi dan tasawuf, dan titik perselisihannya terletak pada fikih dan politik. Dengan kata lain bahwa, teologi membahas tentang masalah-masalah ketuhanan, sementara fikih adalah pelbagai pendapat manusia mengenai kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang menjelaskan tentang `ibâdât (=hubungan manusia dengan Tuhan) atau mu`âmalât (=hubungan manusia dengan manusia). Saya tetap percaya bahwa Islam merupakan sekumpulan ajaran Tuhan yang diturunkan kepada seluruh makhluk, dan saya yakin seluruh kaum Muslimin sepakat dengan saya. Hanya saja, ajaran-ajaran Tuhan tersebut tidak akan dikenal oleh manusia kecuali melalui penafsiran yang tak lain adalah aktivitas manusia itu sendiri. Karena kualitas akal manusia berbeda-beda, maka hasil penafsirannya pun tidak seragam. Sehingga tidak heran kalau setiap kelompok atau mazhab mempunyai pendapat sendiri-sendiri mengenai tata cara pelaksanaan `ibâdât dan mu`âmalât tadi. Namun demikian, teologi yang dipakai seluruh umat Islam, betapapun terkadang terdapat perbedaan dalam menggambarkan entitas Tuhan, toh mereka tetap mengakui teologi tauhid, yaitu peng-esaan Allah swt.. Ini artinya, betapapun fikih yang dianut berbeda-beda, tetapi Tuhan tetap satu.
Di dalam buku ini juga, seperti saya singgung di atas, tasawuf didekatkan dengan politik. Tasawuf adalah upaya manusia untuk membersihkan atau menyucikan segala noda dan dosa yang menempel serta mengotori jiwa, yang tujuan akhirnya adalah mendekati, berdialog dan menyatu dengan Tuhan. Dan pendekatan yang dilakukan bukan dengan teki-teki rasional sebagaimana para ahli kalam, melainkan dengan cinta yang muncul dari hati yang suci. Adapun politik adalah “alat” yang senantiasa digunakan untuk mendapatkan kekuasaan, baik secara halus maupun dengan kekerasan. Perjalanan sejarah Islam selalu saja diwarnai dengan konflik antarkelompok, terutama Syi`ah dan Ahl al-Sunnah, yang pada akhirnya dimenangkan oleh Ahl al-Sunnah, karena kelompok ini berhasil memegang kendali politik. Kesuksesan secara politik ini lantas mereka campur-aduk dengan kebenaran dogmatik agama, sehingga secara agresif mereka berhasil memonopoli pemahaman Islam yang benar (=ortodoksi), tentu saja demi kepentingan mereka sendiri. Sementara kelompok yang tidak sealiran dilempar begitu saja ke jurang heretodoksi.
Namun, di tengah-tengah percaturan politik yang nampak tidak adil itu, terdapat sejumlah orang yang secara sengaja mengasingkan diri, mencari sepercik kedamaian pada sudut-sudut dunia. Tuhan yang bagi manusia biasa mustahil dicapai, coba mereka hadirkan dalam jiwa, mengiringi setiap deraian nafas, tuk hapuskan segala dahaga, dan mengisi pelbagai macam kehampaan. Mereka adalah para sufi yang secara tulus menyembah Tuhan, menyembah-Nya dengan segenap cinta. Setiap saat mereka berdialog dengan-Nya, menumpahkan kegelisahan-kegelisahan batin, mencurahkan berjuta kerinduan yang menghimpit.
Mereka inilah yang kemudian mengajak manusia untuk instrospeksi diri, melihat siapa dirinya yang sesungguhnya, bertanya apa sebenarnya tujuan hidupnya. Politik bukanlah tujuan hidup, ia tak lebih dari sekedar alat. Pada dasarnya memang tidak salah seseorang berkecimpung dalam dunia politik, hanya saja jika pilihan hidupnya diimbangi dengan sikap kritis, karena bagaimanapun politik adalah buatan manusia yang relatif, serba kekurangan. Relativitas politik sangat berpotensi memunculkan pelbagai konflik berdarah. Di sinilah spirit sufistik sangat diperlukan demi mewujudkan adanya sikap saling mengerti, saling menerima dan saling menghormati satu sama lain, sehingga integralitas umat yang selama ini menjadi harapan nantinya akan benar-benar tercapai.
Tentunya spirit sufistik yang dimaksud bukanlah spirit yang “mandul”, atau spirit yang selama ini diasumsikan sebagai penyebab mundurnya peradaban agama dan manusia, tetapi spirit yang dinamis dan menggerakkan. Bukan spirit yang membuat seseorang berhenti menjalin kontak dengan sesamanya, melainkan spirit yang mempunyai kepekaan sosial yang tinggi.
Kalau ditinjau lebih jauh, dalam buku ini kita akan melihat banyak sekali indikasi yang mengarah pada proses terciptanya ijtihad baru, sebuah aktivitas penalaran yang selama ini ramai dibincangkan oleh para tokoh Islam, sebut saja di antaranya adalah Muhammad Iqbal. Menurutnya “ijtihad” merupakan prinsip gerakan dalam Islam. Gerakan yang dimaksud adalah gerakan ke arah sesuatu yang lebih baik atau yang lebih maju. Sebab ijtihad sendiri artinya berusaha dengan sungguh-sungguh. Dalam istilah fikih kata ini berarti berusaha dengan tujuan melakukan suatu penalaran rasional yang bebas perihal suatu persoalan hukum. Kiranya ini sesuai dengan semangat yang terkandung dalam sebuah ayat al-Qur’an yang berbunyi: “Dan kepada mereka yang berusaha kami tunjukkan jalan kami.” Juga ayat lain yang senada: “Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali mereka mau merubahnya sendiri.” Ini dipertegas oleh sebuah hadis yang menceritakan tentang pengangkatan Mu`adz sebagai gubernur Yaman oleh Nabi. Diceritakan bahwa Nabi bertanya kepada Mu`adz bagaimana seyogyanya ia mengambil keputusan mengenai persoalan yang dihadapinya. “Saya akan menjalankan hukum berdasarkan al-Qur’an,” kata Mu`adz. “Tapi jika dalam al-Qur’an tidak ada petunjuk bagimu?” “Saya akan jalan dengan berpijak pada Sunnah.” “Tapi kalau dalam Sunnah juga tidak ada?” “Saya akan berusaha menurut penalaran saya sendiri.”
Dua ayat sebelumnya, secara tidak langsung, menyuruh kita untuk senantiasa berusaha tanpa henti. Sebab hanya dengan berusaha Tuhan akan mengulurkan “tangan-Nya” membantu kita. Sementara hadis setelahnya menjelaskan tentang pedoman yang harus dijadikan pijakan dasar dalam mengarungi kehidupan. Hubungan antara kedua ayat dengan hadis tersebut menjadi sangat jelas, bahwa manusia harus berusaha untuk terus berubah, bergerak ke arah yang lebih baik. Dan dalam menjalani hidupnya, manusia memerlukan pedoman yang bisa dijadikan sandaran. Pedoman tersebut bisa berupa teks-teks agama, seperti al-Qur’an dan hadis, tapi ini saja tidak cukup, manusia masih membutuhkan pedoman lain yang tidak kalah pentingnya dari sekedar teks-teks agama, yaitu akal. Nabi tidak akan bertanya lebih lanjut perihal apa yang harus dilakukan jika ternyata al-Qur’an dan hadis sudah mencukupi dalam proses perumusan hukum. Justru pertanyaan terakhir yang beliau ajukan itu menunjukkan bahwa al-Qur’an dan hadis masih memiliki keterbatasan. Pada titik inilah akal mempunyai peran yang sangat signifikan. Untuk mengaktivasi akal, ijtihad yang oleh Iqbal dianggap sebagai “prinsip gerakan” harus diberlakukan, tidak boleh tidak.
Di samping itu, buku ini juga menyajikan semacam dekonstruksi-rekonstruksi; rancang-bangun teologi, fikih, tasawuf dan politik sengaja dikritik dengan menelusuri latar belakang sejarahnya, setelah itu baru kemudian dilakukan “pembangunan kembali” agar sesuai dengan semangat-semangat modernitas. Nah, setidaknya, “Spirit Modernitas; Paradigma Islam Integral” sudah cukup mewakili untuk menjadi judul buku yang sangat sederhana ini.
************
Sebagian orang barangkali ada yang bertanya, kenapa kami harus capek-capek menulis artikel untuk kemudian dikodifikasikan dalam sebuah buku? Kita perlu melihat masa lalu kita dengan kaca mata masa kini, bukan sebaliknya. Sebagian dari kita ada yang senang mewarnai kehidupan kita saat ini dengan hiasan-hiasan masa lalu, ini adalah sikap yang tidak selaras dengan logika sejarah. Perlu diingat, di hadapan kita ada dua peradaban, peradaban “nenek moyang” kita di satu sisi, dan peradaban masa kini di sisi lain, akan tetapi kedua peradaban ini saling bertolak belakang, sehingga kita tidak mungkin bisa menerima keduanya sekaligus. Peradaban pertama, secara mendasar berkutat pada moralitas-moralitas perilaku yang diridhai Tuhan Yang Maha Esa, sementara peradaban kedua berkutat pada saint berikut bidang-bidang pekerjaan yang dihasilkannya. Peradaban pertama adalah peradaban “teks”, sedang yang kedua adalah peradaban “alat”. Peradaban pertama menghasilkan manusia-manusia yang seragam, adapun yang kedua menghasilkan pabrik-pabrik serta roket-roket yang menari-nari di angkasa. Di sini kita dituntut supaya mampu menyelaraskan keduanya. Ini adalah hal yang tidak pernah ditargetkan oleh Barat, sebab ia hanya memiliki satu peradaban; peradaban modern seperti yang kita lihat saat ini. Kita mengambil dari peradaban Barat apa yang bisa kita ambil, bahwa kita kalau ingin berubah dan membentuk peradaban baru, kita harus merubah standar-standar atau pola-pola yang sudah tidak sesuai dengan kehidupan kita saat ini, maka demi terwujudnya perubahan itulah kami menulis.
Perlu disampaikan di sini, bahwa penulis itu bisa dikelompokkan menjadi dua, sebagian ada yang menulis apa yang ingin dibaca oleh banyak orang, sebagian yang lain ada yang menulis apa yang harus diketahui oleh para pembaca. Kelompok pertama menulis dengan tujuan mencari kerelaan dari para pelanggannya, sedang kelompok kedua hanya memberikan arahan dan petunjuk meskipun harus menuai kemarahan dan kebencian dari banyak orang. Kelompok pertama adalah pemegang cermin agar pada permukaannya bisa memantulkan gambaran manusia sebagaimana adanya, adapun kelompok kedua adalah pemegang lampu guna menerangi jalan di hadapan manusia; jalan baru yang sebelumnya kurang atau bahkan tidak terpikirkan sama sekali (=allâ mufakkar fîhi). Dan kami telah memilih —meskipun sulit— untuk menjadi seperti kelompok kedua, sebab kami senantiasa berusaha menuju ke arah tatanan kehidupan yang lebih baru.
Tak soal kami menulis untuk siapa, kami tidak punya hak untuk memilih pembaca, kami hanya menulis bagi siapa saja yang sudi membacanya. Dan kami tidak bisa mengklaim bahwa kami mampu melenyapkan segenap kegelisahan yang ada di masyarakat, bahkan mungkin, dengan apa yang kami tulis ini, justru akan menambah kegelisahan-kegelisahan lain. Kami tidak ingin menjadi penjilat atau mencari muka, jika kami melihat masyarakat —yang kami adalah bagian dari mereka— merasa perlu untuk melakukan perubahan, maka kami persembahkan buku ini dalam rangka menunaikan amanah pemikiran. Perkara nanti apa yang kami tulis salah atau benar, itu adalah soal lain, yang jelas kami telah berusaha menorehkan pemikiran kami dengan penuh ketulusan.
Itulah sekedar pengantar dari saya selaku editor. Mewakili kawan-kawan SAS Center, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran proses penerbitan buku ini. Kami juga mohon maaf jika dalam buku ini terdapat banyak sekali kekurangan, justru hal itu menunjukkan bahwa kami hanyalah manusia biasa yang tak kebal kesalahan. Akhirnya kritik dan saran konstruktif tetap kami tunggu dari para pembaca, biar untuk ke depan kami bisa berbuat yang lebih baik.
